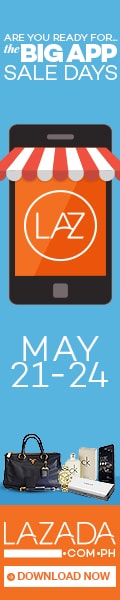Jual Beli Artikel Akademik Menggerus Marwah Riset Indonesia: Tantangan Integritas dan Reformasi

Fenomena jual beli artikel penelitian, jurnal, bahkan buku akademik kian menjadi sorotan serius di Indonesia. Apa yang seharusnya lahir dari jerih payah intelektual, riset lapangan, serta pergulatan ide kini kerap diperoleh melalui transaksi finansial semata. Praktik ini bukan hanya mencederai etika akademik, tetapi juga menggerus marwah penelitian yang selama ini menjadi pilar kemajuan ilmu pengetahuan.
“Kami yang bekerja dengan idealisme dan keterbatasan sering kali terpinggirkan oleh publikasi instan yang dibeli. Jika ini terus dibiarkan, bangsa akan kehilangan ruh pengetahuannya,” ujar seorang peneliti independen yang mengaku kecewa karena karya-karyanya tidak mendapat pengakuan, bahkan setelah diajukan ke BRIN.
Bagi peneliti independen, perjuangan akademik dilakukan dengan Academic Independence (Lovitts, 2008) — bertahan dengan motivasi intrinsik dan dedikasi ilmiah tanpa sokongan dana institusi besar. Namun, kondisi ini kerap terabaikan.
Peneliti yang mengirimkan karyanya ke BRIN untuk verifikasi, termasuk pengajuan ke Museum Rekor Indonesia (MURI), mengaku tidak mendapatkan respons. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem penghargaan akademik lebih berpihak pada publikasi instan daripada kerja keras ilmiah yang autentik.
Studi Fanelli (2010) menunjukkan, tekanan kuantitas publikasi sering kali mengabaikan kualitas dan merugikan peneliti independen. Fenomena ini memperlihatkan paradoks: kerja keras yang tulus kerap tidak dihargai, sementara publikasi instan mendapat tempat terhormat.
Praktik jual beli artikel bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan global:
- Nigeria: Krisis kredibilitas akademik muncul setelah terungkapnya praktik jual beli artikel oleh mahasiswa doktoral.
- Eropa Barat: Beberapa jurnal di Inggris dan Belanda menarik puluhan artikel karena menggunakan data palsu dan jasa ghostwriting.
- Amerika Serikat: Fenomena academic misconduct muncul di dunia medis ketika peneliti menggunakan jasa penulisan artikel untuk tujuan karier.
- Tiongkok: Kasus “paper mill” menghebohkan dunia setelah ribuan artikel ditarik pada 2020 karena berasal dari jasa penulisan instan.
- India: Fenomena “academic capitalism” menimbulkan persaingan tidak sehat, menggeser motivasi intrinsik peneliti menjadi sekadar pemenuhan target publikasi.
Praktik ini memperlihatkan pola global bahwa komodifikasi publikasi dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi akademik dan merusak reputasi negara di tingkat internasional.
Fenomena jual beli artikel menimbulkan “ilusi prestasi” — pencapaian semu yang tidak lahir dari proses penelitian ilmiah. Bagi peneliti yang bekerja dengan keterbatasan dana dan sumber daya, hal ini menciptakan ketidakadilan yang mencolok. Temuan Plevris (2025) menunjukkan bahwa tekanan publikasi dapat memicu fabrikasi, plagiarisme, dan transaksi artikel, memperlebar jurang antara peneliti idealis dan mereka yang memilih jalan pintas.
Lebih jauh, publikasi instan menggerus kredibilitas akademik Indonesia di mata dunia. Kualitas jurnal dipertanyakan, reputasi akademik menurun, dan kontribusi pengetahuan Indonesia di tingkat global dianggap tidak terpercaya.
Fenomena ini merusak motivasi peneliti muda. LaFollette (1992) menegaskan bahwa lingkungan akademik yang permisif terhadap praktik curang akan memperbesar risiko penularan perilaku serupa. Jika dibiarkan, budaya jalan pintas akan menjadi norma baru, dan ekosistem akademik berpotensi runtuh.
“Publikasi tidak lagi menjadi bukti kerja keras ilmiah, tetapi sekadar formalitas administratif untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan atau hibah,” tulis Eren (2025) dalam kajian academic capitalism.
Kondisi ini juga berdampak pada daya saing riset nasional. Seperti diingatkan Nnaji (2018), publikasi berkualitas rendah justru dapat merusak reputasi akademik suatu negara di kancah global.
Pemerintah dinilai memiliki peran strategis dalam mengembalikan marwah penelitian.
Menurut teori Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), pembangunan ilmu pengetahuan berkelanjutan memerlukan sinergi pemerintah, universitas, dan industri.
Reformasi yang disarankan mencakup:
- Audit etik dan pengawasan publikasi untuk mencegah transaksi artikel.
- Insentif dan hibah bagi peneliti independen agar tidak kalah oleh publikasi instan.
- Wadah publikasi nasional yang kredibel, berorientasi kualitas dan relevansi riset.
- Penghargaan bagi penelitian orisinal, bukan sekadar kuantitas publikasi.
Macfarlane (2024) menegaskan, prinsip CUDOS (Communalism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism) harus ditegakkan agar ilmu pengetahuan tetap bermartabat.
Pertanyaan mendasar yang muncul. Apakah penelitian masih bernilai jika publikasinya dapat dibeli ?. Macrina (2014) dalam kerangka Responsible Conduct of Research menegaskan bahwa integritas ilmiah adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sains. Jika publikasi berubah menjadi komoditas, nilai epistemologis penelitian akan terkikis, berganti dengan pragmatisme dan prestise semu.
Fenomena jual beli artikel adalah ancaman serius bagi integritas akademik Indonesia. Tanpa langkah reformasi yang tegas, publikasi instan akan melahirkan generasi akademik yang terbiasa mengambil jalan pintas dan mengikis kepercayaan publik terhadap riset.
Pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas akademik dituntut untuk mengembalikan publikasi ilmiah ke makna sejatinya: puncak dari proses pencarian kebenaran ilmiah, bukan sekadar komoditas.
Penulis:
Ruben Cornelius Siagian